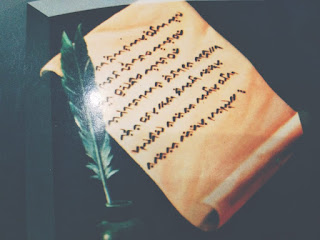“
Iko anang appoku, sikadedattakko,
Tassitajan
kaliuloakko, sisala
Makale’ko
sikabudaan karuekko,
sisala
karuekko sikabuda makaleo’ko, iko to andi paandi-i
kalemu
iko tokaka pakakai kalemu,
pakalabii
inde tomatoammu, dau
kuanni
anangngu : ‘tau asu’ atau
‘puapakotuu’.”
***
Entah
apa yang membuat generasi sekarang sulit berkomunikasi dengan santun antar
sesamanya. Umpatan dan makian silih berganti masuk dan keluar dari telinga
kita. Tutur kata yang ramah seakan mahal harganya. Bahkan, umur tidak lagi
menjadi batasan dimana yang kecil bisa berlaku semaunya dan yang tua
merajalela. Bosan dengan cacian yang standar, kata-kata kasar kini mulai
membawa-bawa nama makhluk lain diantara perdebatan. Makhluk itu bernama hewan.
Perbedaan
budaya bukan alasan untuk menanggalkan tradisi saling menghargai sesama
manusia. Budaya dan tradisi malah bisa memperkuat hubungan persaudaraan
diantara dua suku yang berbeda. Apalagi bila yang berkomunikasi itu adalah dua
individu dengan budaya yang sama.
Dahulu kala, bahkan untuk mempererat jalinan persaudaraan antara budaya- budaya yang berbeda, raja-raja melakukan perjanjian sebagai pondasi untuk saling memuliakan satu sama lain. Selain itu, dengan perjanjian-perjanjian tersebut, generasi mereka dapat saling berbaur dan bekerjasama tanpa harus dibatasi oleh budaya dan aturan-aturan yang memberatkan.
Dahulu kala, bahkan untuk mempererat jalinan persaudaraan antara budaya- budaya yang berbeda, raja-raja melakukan perjanjian sebagai pondasi untuk saling memuliakan satu sama lain. Selain itu, dengan perjanjian-perjanjian tersebut, generasi mereka dapat saling berbaur dan bekerjasama tanpa harus dibatasi oleh budaya dan aturan-aturan yang memberatkan.
Di
masyarakat Kabupaten Enrekang pun demikian. Menurut sejarah, sekitar abad ke-14
M, 6 raja berkumpul di kampung Leoran, sekitar 4 kilometer dari Kota Enrekang. Mereka
adalah Addatuang Sawitto, Puang Makale, Puang Baroko, Puang Taulan, Aru’ Belawa,
dan Puang Letta. Pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan dalam bentuk
perjanjian bahwa enam raja tersebut “bersaudara”.
Awal Mula Penyematan Kata-Kata Kasar :
Awal Mula Penyematan Kata-Kata Kasar :
Puang Leoran ketika itu memelihara “Tau Asu” yakni mahkluk yang bagian
kepala hingga perutnya berwujud manusia, sedang bagian perut hingga kakinya
menyerupai anjing. Hingga kini masih saja ada masyarakat
Enrekang ketika tidak mampu menahan amarahnya, akan mengucapkan kata-kata kasar
dengan penuh luapan emosi. Memandang saudaranya sendiri sebagai binatang atau “tau
asu” (manusia tapi memiliki sifat seperti anjing). Pada
akhirnya, La Tanro P. Janggo Puang Kali Endekang (Aru Buttu), menurut catatan
lontarak Enrekang, berwasiat:
“
Iko anang appoku, sikadedattakko,
Tassitajan
kaliuloakko, sisala
Makale’ko
sikabudaan karuekko,
sisala
karuekko sikabuda makaleo’ko, iko to andi paandi-i
kalemu
iko tokaka pakakai kalemu,
pakalabii
inde tomatoammu, dau
kuanni
anangngu : ‘tau asu’ atau
‘puapakotuu’.”
Artinya
:
“ Wahai anak
cucuku, agar kalian saling mengasihi, jangan menyimpan dendam dan dengki. Bila kalian
bertengkar di waktu pagi, rukun kembali di waktu sore, bila kalian bertengkar
di waktu sore, rukun kembali di waktu pagi. Yang adik tempatkan dirimu sebagai
adik dan yang kakak tempatkan dirimu sebagai kakak. Dan jangan pernah lupa
menghormati kedua orang tuamu. Pesanku yang terakhir, jangan mengatakan ‘anjing’
(tau asu) atau ‘tak ada gunamu’ (taen gunana te’pea) kepada anak-anakmu dan
keturunanmu”
Sumber
referensi : Buku karya H. Puang Palisuri ( 2005) Perjanjian Bersaudara Sawitto dan Enrekang
diterbitkan oleh Yapensi Jakarta.